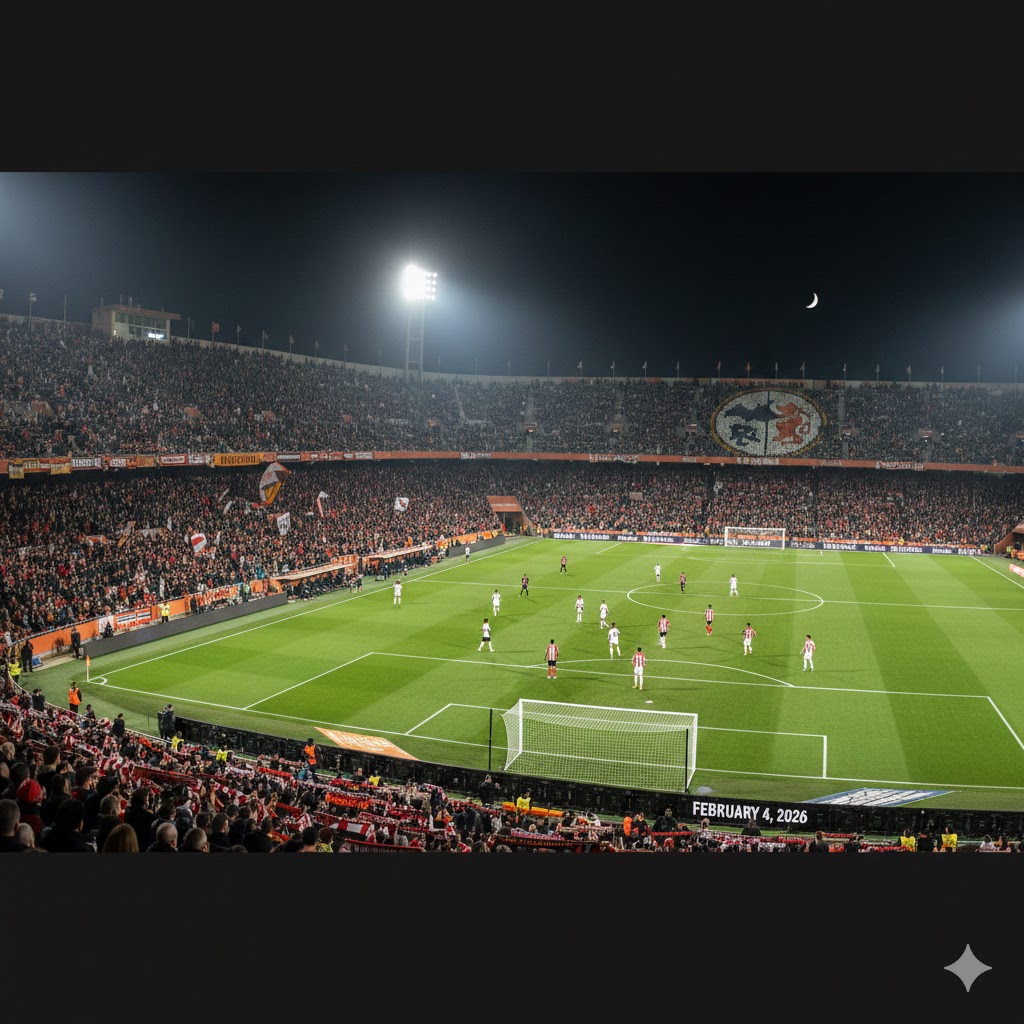Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial di Indonesia diguncang oleh satu nama besar: Pandji Pragiwaksono—komika, penulis, dan pembawa acara yang dikenal tajam dalam satire politiknya. Lagu-lagu rap, acara TV, hingga monolog stand‑up biasa saja—namun kali ini, satu materi komedi spesialnya meledak menjadi peperangan opini publik, karena menyinggung sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Materi itu dipertontonkan dalam acara stand‑up comedy bertajuk “Mens Rea” yang dirilis di platform streaming besar akhir Desember 2025 lalu. Tayangan berdurasi lebih dari dua jam itu ternyata tidak hanya menjadi tontonan hiburan, tapi juga bahan diskusi panas yang membuat Pandji jadi trending topic dan memicu pro‑kontra yang luas di ruang publik.

Pandji dan Sindiran yang Memicu Riuh
Salah satu klip paling viral dari “Mens Rea” adalah ketika Pandji berbicara tentang fenomena pemilih yang memilih pemimpin berdasarkan penampilan fisik. Ia mengulang beberapa contoh — seperti “Ganjar, ganteng ya”, “Anies, manis ya” — lalu menyelipkan komentar tentang Gibran.
“Kita semua tahu, ada yang pilih pemimpin karena tampang… atau, wakil presidennya… Gibran ngantuk ya,” ucap Pandji di atas panggung, disambut gelak tawa penonton.
Kalimat ringan tersebut ternyata menjadi bahan bakar bagi percikan pro dan kontra di jagat maya. Bukan hanya soal kritik politik biasa, tetapi berujung pada evaluasi lebih dalam tentang batas-batas humor, kebebasan berekspresi, hingga sensitivitas terhadap figur publik.
Pandji Reaksi dari Gibran Sendiri
Berbeda dari dugaan sejumlah pihak, Gibran Rakabuming Raka sendiri menyikapi sindiran Pandji dengan santai dan bijak. Dalam sebuah kesempatan, Wapres menyatakan bahwa kritik seperti itu adalah bagian dari evaluasi publik yang wajar dan dapat diterima sebagai bahan introspeksi.
“Kritik evaluasi itu biasa,” ujar Gibran, menunjukkan sikap dewasa dalam kontestasi opini publik yang kian dinamis.
Respons seperti ini justru memperlihatkan dua hal: pertamanya, tidak keberatan figur publik terhadap satire politik; dan kedua, kenyataan bahwa isu ini lebih meruncing di kalangan netizen ketimbang di lingkup pemerintahan sendiri.
Pandji Pro Kontra yang Meledak di Medsos
Reaksi netizen terhadap kata “ngantuk” tadi bervariasi drastis. Beberapa mendukung kebebasan berekspresi komika yang kritis terhadap pejabat publik. Mereka melihat satire semacam ini sebagai bagian dari demokrasi sehat dan diskusi politik kreatif.
Namun, tidak sedikit juga yang menganggap komentar tersebut sebagai pelampiasan yang kurang elok, bahkan sampai mengejek fisik seseorang yang seharusnya bukan bahan lawak. Kritik tajam datang dari berbagai figur publik, termasuk dr. Tompi, yang menyebut menertawakan kondisi fisik bukanlah bentuk kritik yang cerdas.
Tompi bahkan menyatakan bahwa kondisi fisik semacam kelopak mata yang terlihat “ngantuk” memiliki istilah medis tersendiri dan bukan hal yang layak dijadikan punchline. Pernyataan ini lantas ikut viral di platform Instagram, memancing komentar panjang dari netizen.
Isu Hukum dan Pendapat Pakar
Tidak berhenti hanya di komentar netizen, masalah ini sempat dikaitkan dengan kemungkinan jeratan hukum. Artikel berita ramai membahas bahwa materi Pandji tersebut bisa saja masuk unsur penghinaan pejabat negara berdasarkan KUHP baru yang mulai berlaku Januari 2026.
Namun, pandangan ahli hukum tidak membenarkan itu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa dalam konteks ini, Pandji tidak bisa dipidana atas Apa yang ia sampaikan — sekalipun merujuk pada pasal-pasal penghinaan. Bahkan Mahfud menyatakan siap membela Pandji jika diperlukan.
Menurut Mahfud, pernyataan komika itu termasuk dalam hak kebebasan berpendapat dan komentar satir, yang secara hukum tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Ia juga menyarankan agar isu pasal‑pasal ini ditinjau ulang secara konstitusional jika berpotensi mengekang ekspresi publik.
Buzzer dan Gelombang Diskusi
Seiring perdebatan menguat, banyak pihak yang memperhatikan fenomena “buzzer bergerak” setelah video stand‑up Pandji jadi viral. Sejumlah akun dan kelompok netizen aktif membela atau menyerang Pandji melalui tagar, komentar, dan unggahan beragam.
Pandji sendiri sempat mengomentari gegap gempita itu di akun media sosialnya dengan nada santai namun pedas, menyebut bahwa ada pihak yang terlalu triggered dan mengeluarkan energi lebih besar daripada yang diperlukan.
Mana Batas Humor dan Kebebasan Berekspresi?
Kasus Pandji dan Gibran ini pada akhirnya membuka diskusi besar tentang batas‑batas humor, kritik terhadap figur publik, serta ruang ekspresi di era digital. Apakah satire semacam ini sehat untuk demokrasi? Atau justru menjadi bumerang ketika mengarah ke hal yang dianggap pribadi dan sensitif?
Satu hal yang pasti: isu ini bukan sekadar soal satu kalimat di atas panggung. Ia berkaitan dengan cara masyarakat memaknai kritik, debat, serta ekspresi kreatif di ruang publik yang semakin terbuka dan tanpa batas. Dengan atau tanpa persetujuan semua pihak, debat ini menunjukkan betapa kuatnya perkusi opini di era media sosial yang kian terintegrasi dengan ruang politik dan budaya populer.